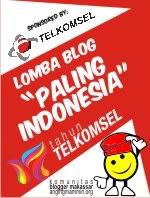Tontonan Jadi Tuntunan, Tuntunan jadi Tontonan
antara Budaya dan Agama
antara Budaya dan Agama
Pernahkah Anda melihat kotoran kerbau bule dibalurkan ke tubuh seseorang agar dapat berkah, atau air cucian kereta dan keris jadi rebutan agar berlimpah rejeki, itulah tontonan yang jadi tuntunan. Tetapi di sisi lain Pengajian jadi tontonan misalnya "Dai sejuta Umat"
Salah satu acara yang mengundang banyak orang di daerah Solo adalah arak-aran kebo bule yang mengiringi pusaka keraton setelah jamasan (mencuci pusaka keraton ) yang dilakukan di malam 1 suro. Acara ini sudah masuk dalam kalender wisata kota Solo yang dipadati oleh masyarakat. Acara ini diawali dengan dikeluarkannya pusaka keraton dari keris sampai tombak untuk dijamas/dicuci setahun sekali.
Pusaka Keraton Solo ini dicuci dengan air jeruk nipis dan berbagai bunga/kembang sebagai pelengkap. Maksud dari pencucuian ini adalah untuk menghindarkan pusaka ini berkarat dan cukup dilakukan setahun sekali dengan cairan karena apabila terlalu sering malah merusak bahan dari pusaka. Air bekas dari cucian pusaka inilah yang diperebutkan masyarakat untuk cuci muka ataupu untuk dibawa ke rumah dan di siramkan ke sawah ladang mereka biar panen. Padahal dari pihak Keraton menyatakan air tersebut tidak mempunyai manfaat apapun. Selanjutnya pusaka ini dibawa keliling keraton diikuti dengan kebo bule (kerbau albino berwarna putih). Kerbau ini begitu keramat di kalangan keraton sehingga sangat terpelihara dengan baik. Sepanjang jalan yang dilalui arak-arakan pusaka dan kebo bule yang dilakukan malam hari ini, masyarakat telah berdiri sepanjang jalan. Sebagai tradisi budaya memang tidak mengherankan jika masyarakat begitu antusias menantinya. Sepanjang jalan yang dilalui kebo bule ini tidak jarang kerbau ini mengeluarkan kotoran di aspal jalan, herannya masyarakat khususnya dari pedesaan memungut kotoran kerbau ini ada yang di simpan di kantong plastik bahkan ada yang membalurkannnya di anggota badan mereka untuk mengharap berkah, tentunya semua ini hanya ada di Indonesia.
Pusaka Keraton Solo ini dicuci dengan air jeruk nipis dan berbagai bunga/kembang sebagai pelengkap. Maksud dari pencucuian ini adalah untuk menghindarkan pusaka ini berkarat dan cukup dilakukan setahun sekali dengan cairan karena apabila terlalu sering malah merusak bahan dari pusaka. Air bekas dari cucian pusaka inilah yang diperebutkan masyarakat untuk cuci muka ataupu untuk dibawa ke rumah dan di siramkan ke sawah ladang mereka biar panen. Padahal dari pihak Keraton menyatakan air tersebut tidak mempunyai manfaat apapun. Selanjutnya pusaka ini dibawa keliling keraton diikuti dengan kebo bule (kerbau albino berwarna putih). Kerbau ini begitu keramat di kalangan keraton sehingga sangat terpelihara dengan baik. Sepanjang jalan yang dilalui arak-arakan pusaka dan kebo bule yang dilakukan malam hari ini, masyarakat telah berdiri sepanjang jalan. Sebagai tradisi budaya memang tidak mengherankan jika masyarakat begitu antusias menantinya. Sepanjang jalan yang dilalui kebo bule ini tidak jarang kerbau ini mengeluarkan kotoran di aspal jalan, herannya masyarakat khususnya dari pedesaan memungut kotoran kerbau ini ada yang di simpan di kantong plastik bahkan ada yang membalurkannnya di anggota badan mereka untuk mengharap berkah, tentunya semua ini hanya ada di Indonesia.
Kirab pusaka beserta jamasan pusaka juga ada di keraton Jogja, tetapi ada acara budaya yang mengambil dari kegiatan ibadah yaitu tradisi Mubeng Benteng Kraton (Keliling benteng Kraton dengan berjalan kaki). Sebenarnya tradisi Mubeng Benteng ini mengambil dari kegiatan Towaf mengelilingi Ka'bah sabagai rukun dari haji. Mubeng benteng ini dilakukan masyarakat di malam hari dan dilarang berbicara selama melakukan ritual ini. Kegiatan ini begitu mengakar di masyarakat Jogja, tetapi Sultan sendiri sebagai raja kraton jogja jarang terllihat bahkan tidak melakukan tradisi ini. Masyarakat mempercayai apabila telah melakukan ritual budaya ini mereka akan selamat dan dilimpahi banyak rejeki. Keraton Solo dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah kerajaan Islam, yang tidak heran segala macam ritual budayanya bernafaskan ajaran Islam. Ajaran Islam ini sebenarnya diselipkan di budaya keraton sebagai syiar agama. Tetapi tradisi ini begitu mengakar sehingga yang tadinya hanya sebagai pemanis dianggap sebagai tuntunan. Sehingga tidak heran masyarakat lebih mendahulukan tradisi daripada nilai ibadah.